Oleh: Dedet Zelthauzallam
Arus globalisasi dewasa ini sepertinya tidak bisa
dibendung. Globalisasi memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan
suatu negara. Tantangan, peluang dan ketergantungan antar negara semakin
meningkat. Era globalisasi ini semakin terasa dengan didukung oleh kemajuan
ilmu pengetahuan dan tehnologi informasi yang berkembang pesat, yang membuat
dunia ini seolah-olah tanpa batas (borderless
world). Dalam sekejap setiap peristiwa penting yang terjadi pada satu
belahan dunia dapat diketahui oleh warga masyarakat di belahan dunia lainnya. Dalam
situasi seperti ini, dituntut kemampuan presiden sebagai pimpinan suatu negara
untuk bisa melihat dan menghadapi perubahan, dengan mempersiapkan segala
sesuatu yang diperlukan dalam mengantisipasi situasi dinamika yang terjadi,
baik dalam konteks negara maupun dalam pola hubungan dengan bangsa lain. Namun,
dalam mengakomodir pola hubungan luar negeri, juga dibutuhkan kemampuan
filterisasi dalam menjaga karakter
bangsa dan negaranya.
Presiden adalah nahkoda utama dari suatu negara. Dengan
peran sebagai nakhoda tersebut, maka negara akan sangat bergantung pada
bagaimana kemampuan presiden dalam mengelola dan menata pemerintahan. Kemampuan
presiden yang dimaksud, dapat berupa kapabilitas,
integritas dan akuntabilitas, sehingga bisa menjalankan amanah yang
dipercayakan kepadanya secara efektif dan efesien.
Jika mengacu pada teori kepemimpinan, ciri pemimpin yang
efektif dan efesien adalah mereka yang mampu mengejewantahkan apa yang disebut
akuntabilitas politik, bukan tribalisme politik. Menurut Fukuyama
(2011), pemimpin atau pejabat publik yang mampu menjalankan kepemimpinan secara
akuntabel ialah mereka yang dapat mempertanggungjawabkan kepada rakyat setiap
kebijakan yang telah ditelurkannya. Mereka juga mampu mengutamakan kepentingan
rakyat (publik) di atas kepentingan pribadi kelompoknya. Sedangkan pemimpin yang
tribalistik, yaitu seorang pemimpin yang lebih mementingkan citra dan lebih
mengutamakan diri pribadi dan kelompoknya dari pada rakyatnya[1].
Sepertinya tipe tribalistik menjadi lebih dominan
dilakukan oleh para pemimpin negeri ini, termasuk presiden. Presiden sebagai
kepala negara dan pemerintahan memiliki tanggung jawab yang sangat besar yang
diamanahkan rakyat kepadanya. Namun presiden sering dan malah selalu
mempoligami amanah tersebut. Pasca terpilih menjadi presiden mereka lupa untuk
melepas baju partainya, dalam artian melaksanakan peran ganda, yaitu menjadi
kepala negara dan ketua partai.
Budaya seperti itu sudah dilakukan sejak orde baru sampai
reformasi. Meskipun di era orde baru, Golkar tidak diidentikkan sebagai partai,
tetapi bisa dikatakan memiliki fungsi yang melebihi partai yang dijadikan
Soeharto dan koleganya untuk mempertahankan kekuasaan selama 32 tahun.
Sedangkan di era reformasi, Gusdur (PKB), Megawati (PDIP) dan Susilo Bambang
Yudhoyono (Partai Demokrat) pada saat menjabat presiden, mereka masih berstatus
sebagai ketua umum partai. Tentunya ini akan rentan terjadi “conflict of interest” dan “abuse of power” yang digunakan untuk
kepentingan pribadi, kelompok dan / atau partainya.
Dilihat
dari aspek yuridis, maka peran ganda yang dilakukan ini bisa dikatakan legal,
tidak melanggar konstitusi. Dalam
UUD 1945 dan UU Nomar 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden tidak ada pasal satu pun yang melarang dan menyinggung masalah peran
ganda ini. Namun dari segi etik, maka masalah ini perlu dikaji ulang. Dimana
presiden yang juga bisa dikatakan sebagai manusia biasa memiliki sisi
kerakusan. Dalam istilah Plautus (195 SM) yang dipopulerkan Hobbes, manusia yang
satu sebagai serigala bagi manusia lainnya (homo
homini lupus), adalah sebagai penegasan bahwa manusia itu menganggap
penaklukan terhadap manusia lainnya adalah kodrat.
Menurut Direktur Ekskutif Pol-Tracking Institute, Hanta
Yuda AR, menyatakan bahwa adanya peran ganda yang dimiliki akan menyebabkan
fokus akan terpecah atau disebutnya dengan istilah sebagai dualisme loyalitas,
yakni di satu sisi pada tugas pemerintahan dan disisi lain pada tugas partai
politik. Terdapat pandangan yang memandang miris dualisme peran tersebut,
dengan memandang aspek manfaatnya dalam melaksanakan tugas pemerintahan akan
tergerogoti dengan fungsi lainnya yakni selaku penyelenggara partai politik.
Namun, di sisi lain dapat diinterpretasikan bahwa dualisme ini tidak menjadi
sesuatu yang saling mengorbankan, bilamana tugas utama selaku penyelenggara
pemerintahan tetap menjadi prioritas dalam melaksanakan fungsinya sebagai
presiden.
Situasi dualisme ini semakin menarik untuk dikaji bila
mengamati proses pemilihan presiden yang dipilih secara langsung dengan peran
partai politik itu sendiri. Pemilu langsung memang semakin membuat presiden dan
wakil presiden tidak bisa dipisahkan dari namanya partai politik. Karena partai
politik menjadi kendaraan untuk merebut kursi kekuasaan. Mustahil bagi seorang
tokoh bisa maju sebagai capres dan cawapres tanpa dukungan dari partai politik,
karena dalam pemilihan capres dan cawapres tidak ada istilah jalur independent, tidak seperti pemilihan
kepala daerah. Salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah harus didukung
minimal 20% suara di parlemen atau 25% suara sah nasional. Jadi mau tidak mau,
suka tidak suka, presiden harus melalui partai politik.
Dalam tataran etika pemerintahan, terdapat konsepsi yang
mengarahkan untuk melakukan fokus terhadap satu kegiatan pemerintahan, dengan
mengarahkan bentuk ketegasan dan komitmen dari partai politik untuk mau legowo melepas kader terbaiknya. Hal ini
dimaksudkan semata-mata untuk fokus terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sehingga
bisa mengemban amanah rakyat dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Adagium
yang perlu selalu dipegang, “loyalitasku pada partai berhenti pada saat
pelayananku pada negara dimulai”. Inilah yang harus menjadi slogan bagi partai
dan kader yang terpilih. Jangan sampai partai politik memberikan peran ganda
dan kader yang terpilih tidak mau melepas tahta di partainya.
Apabila mengacu
pada rumusan Lemhanas tentang Indeks Kepemimpinan Nasional Indonesia (IKNI),
maka kriteria pemimpin adalah pertama,
Indeks Moralitas dan Akuntabilitas Individual, kedua, Indeks Moralitas dan Akuntabilitas Sosial, ketiga, Indeks Moralitas dan
Akuntabilitas Institusional, dan keempat,
Indeks Moralitas dan Akuntabilitas Global[2]. Kriteria moralitas dan akuntabilitas menjadi pokok
penting yang perlu diperhatikan dan dimiliki oleh pemimpin masa sekarang dan masa
depan. Moralitas merupakan zat pikir yang ada dalam setiap diri manusia untuk mematuhi
aturan yang diciptakan oleh Tuhan menurut agama dan kepercayaan masing-masing
yang ada dalam setiap orang[3]. Ini berarti moralitas dan akuntabilitas harus berjalan
bersinergi supaya bisa mewujudkan kepemimpinan yang benar-benar amanah dalam menjalankan tugas
dan fungsinya.
Presiden dalam menjalankan tugas dan fungsi hendaknya
harus tetap berkonsentrasi pada penyelenggaraan pemerintahan dan negara saja
demi mempercepat tercapainya tujuan negara yang ada dalam pembukaan UUD 1945,
yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia. Founding father menghendaki konsep negara
Indonesia ialah negara keadilan dan negara kekeluargaan yang bisa dilihat dari basic law, Pancasila. Tentunya ini harus
tetap diwujudkan oleh the next generation,
supaya eksistensi Negara Indonesia untuk bisa mengatasi paham perseorangan dan
golongan yang sangat bhinneka tetap
bisa terwujud tanpa saling meniadakan. Disinilah dibutuhkan peran presiden yang
benar-benar fokus untuk merangkul pluralisme di Indonesia, tanpa mementingkan
individu, kelompok dan / atau partainya.
[1]
Ali Rif’an, “Menyoal Caleg Menteri Parpol” dimuat di http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=337573
[2]
Dr. Adi Sujatno, S.H., M.H dan Drs Asep Suhendar, M.Si, “Konsep Ideal
Kepemimpinan Nasional Nusantara, Menjawab Tantangan Global”, (Jakarta: PT.
Yellow Multi Media, 2013), 87.
[3]
Ermaya Sradinata, “Analisis Kepemimpinan, Strategi Pengambilan Keputusan”,
(Bandung: ALQAPRINT: Oktober 2013), 14.
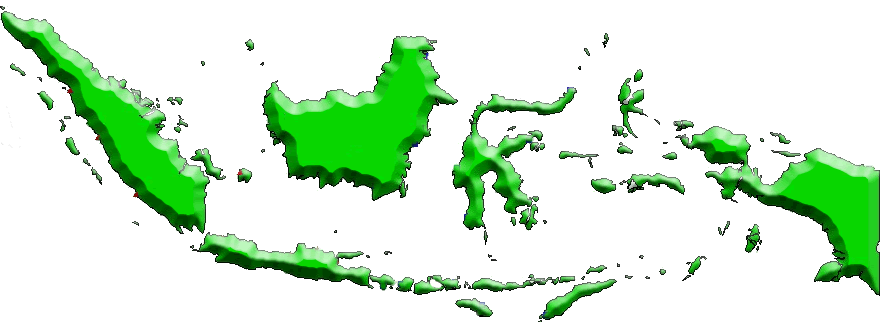





No comments:
Post a Comment