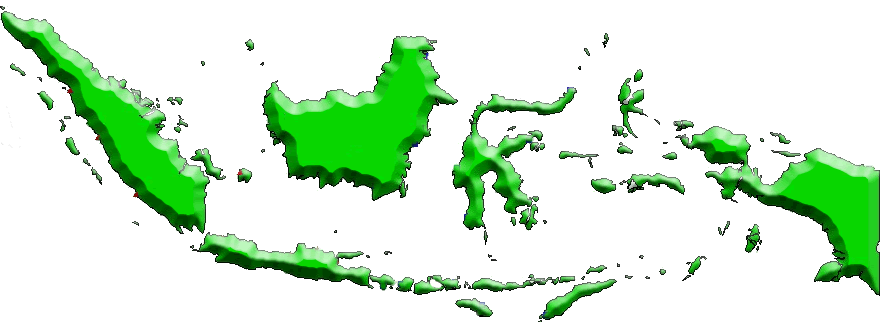Oleh: Dedet Zelthauzallam
Kurikulum
2013 secara serentak diberlakukan pada tahun ajaran 2014/2015 di seluruh
sekolah. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muh. Nuh, yang
mengatakan bahwa sekolah tidak ada alasan untuk tidak menerapkan kurikulum
2013. Pemberlakuan kurikulum 2013 ini sebagai
pengganti dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum KTSP. Dengan
digantinya KTSP menjadi kurikulum 2013 menambah rentetan pergantian kurikulum pendidikan
di Republik ini yang sudah mencapai 11 kali.
Seringnya
pergantian kurikulum di Republik ini diakibatkan oleh tidak adanya parametar
yang jelas mengenai pendidikan. Tidak adanya parameter inilah yang menyebabkan
kurikulum di Republik ini mengikuti kemauan penguasanya. Hal itulah yang
menimbulkan adigium, penguasa berganti kurikulum pun berganti.
Dengan
perubahan kurikulum yang mengikuti penguasa membuat wajah pendidikan di
Republik ini cenderung stagnan. Stagnan karena lebih cenderung bersifat
politis. Politis dalam artian hanya akan berlaku di era pembuatnya.
Tentunya
budaya perubahan kurikulum ini tidak boleh terus menerus dibiarkan. Apabila
dibiarkan, maka otomatis Republik inilah yang akan dirugikan, baik dari segi
materil maupun masa depan manusianya. Dari segi materi misalnya, biaya yang
dibutuhkan untuk pergantian kurikulum mencapai miliaran sampai triliunan
rupiah. Sebagai contoh, pergantian kurikulum 2013 menghabiskan anggaran sekitar
2,49 T. Anggaran yang tersedot tersebut bisa dikatagorikan amat tinggi,
sehingga apabila tidak ada konsep yang jelas akan menyebabkan uang tersebut
mubazir.
Pergantian kurikulum juga membuat tenaga
pengajar (baca: guru) menjadi pusing. Ini diakibatkan oleh buku yang digunakan,
metode pengajaran maupun materinya akan berubah, sehingga diperlukan adaptasi
yang cepat dan tepat dari guru. Namun, yang menjadi permasalahan, guru sulit
untuk beradaptasi, sehingga kurikulum baru secara formal berlaku, tetapi dalam
prakteknya masih menggunakan pola lama.
Revolusi Mental Pada Pemerintahan Baru
Berlakunya
kurikulum 2013 di tahun transisi pemerintahan membuat masa depan kurikulum ini
penuh tanda tanya. Penuh tanda tanya maksudnya adalah apakah kurikulum 2013 ini
sesuai atau tidak sesuai dengan konsep revolusi mental yang didengungkan oleh pemerintahan baru yang
dipimpin Jokowi-JK. Apabila tidak satu nafas, maka otomatis kurikulum yang
bernilai triliunan ini akan mati suri diusia muda.
Melihat
konsep revolusi mental dari Jokowi-JK yang disampaikan pada saat kampanye
pemilihan presiden, maka kurikulum 2013, menurut saya, belum sejalan. Kurikulum
2013 masih belum bisa mengekskusi visi misi pemerintahan baru, karena orientasi
kurikulum ini lebih berorientasi saintifik. Siswa lebih dituntut menemukan
sendiri keilmuan yang ada, tanpa terlalu banyak menggantungkan diri pada
pengajaran guru.
Hal
tersebut tentunya tidak sesuai dengan pendidikan yang dicita-citakan oleh
Jokowi-JK. Sesuai dengan apa yang disampaikan Jokowi pada saat kampanye, pendidikan
harus bernuansa revolusi mental yang akan dimulai dari tingkat pendidikan
dasar. Menurutnya, siswa SD harus lebih banyak diberikan pendidikan karakter,
etika dan budi pekerti, presentasenya sebesar 80%, sedangkan pengetahuan umum
hanya sebesar 20%. Untuk tingkat SMP, porsi materi pengetahuan umum dengan
pendidikan karakter sebesar 40%-60%. Sedangkan untuk SMA, porsi pengetahuan
umum lebih besar dengan presentase 80%-20%. Jokowi juga ingin memperbanyak
sekolah kejuruan yang bisa menghasilkan siswa yang lebih siap terjun langsung
ke lapangan dengan memiliki keahlian yang sudah didapatkan di sekolah.
Dengan
melihat konsep yang diberikan Jokowi, maka konsep pendidikan ke depan lebih mengarah
pada pembangunan karakter, tidak seperti dewasa ini, materi pendidikan lebih
didominasi oleh pengetahuan umum. Pendidikan budi pekerti, menurut saya,
penting diakibatkan oleh masalah yang multidemensi melanda Republik ini berawal
dari kekosongan etika moral masyarakat.
Sebut
saja korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara di Republik ini. Mereka
memiliki latar pendidikan yang tinggi dengan gelar yang tak terhitung. Namun
mereka tetap saja melakukan tindakan korupsi. Ini dilakukan bukan karena mereka
tidak paham atau kebodohannya, tetapi karena mereka tidak memiliki karakter
yang kuat dalam diri mereka, sehingga etika dan moral mereka nol besar.
Kekosongan
etika moral masyarakat perlu dibangun melalui pendidikan. Pendidikan sangat
tergantung pada model kurikulum yang digunakan. Apabila kurikulum yang
diterapkan sesuai dengan kebutuhan, maka akan menciptakan manusia Indonesia
yang memiliki karakter, beretika dan bermoral. Dengan demikian, maka manusia
Indonesia adalah manusia yang bermartabat. Bermartabatnya manusia Indonesia
tentunya akan melepas Indonesia dari berbagai belenggu yang menghalangi
pencapaian cita-cita berbangsa dan bernegara, khususnya cita-cita mencerdaskan.
Dalam
menyusun kurikulum pendidikan, hendaknya pemerintah baru harus mengacu pada
kebutuhan lingkungan internal dan eksternal. Yang dimaksud internal adalah dari
dalam negeri sendiri. Pancasila sebagai dasar negara wajib dijadikan landasan
utama dalam penyusunan kurikulum, supaya nilai-nilai di dalam sila Pancasila,
mulai dari ke-Tuhanan sampai keadilan sosial menjiwai seluruh mata pelajaran.
Selain itu, budaya lokal harus diperhatikan, supaya tidak seperti dewasa ini,
dimana generasinya lebih paham dengan budaya luar dibandingkan budaya sendiri.
Lingkungan
eksternal yang dimaksud adalah dari aras global, karena mau tidak mau, suka
tidak suka, akan ikut mempengaruhi iklim persaingan dalam berbagai hal. Yang
perlu dicatat disini, dalam mengambil acuan pada lingkungan eksternal tidak
boleh merusak lingkungan internal. Artinya, nilai-nilai positif pendidikan yang
sudah berakar di Republik ini tidak boleh tereleminasi dengan adanya nilai baru
yang berasal dari luar.
Kurikulum
ke depannya juga harus memiliki pilar yang kuat. Menurut UNESCO, ada empat
pilar pendidikan sekarang dan masa depan yang perlu dikembangkan oleh lembaga
pendidikan formal, yaitu 1) learning to
know (belajar untuk mengetahui), 2) learning
to do (belajar untuk melakukan sesuatu), 3) learning to be (belajar untuk menjadi seseorang), dan 4) learning to live together (belajar untuk
menjalani kehidupan bersama). Empat pilar pendidikan dari UNESCO ini harus
menjadi refrensi bagi pendidikan di Republik ini.
Pendidikan
masa depan tidak menciptakan manusia robot, tetapi menelurkan manusia-manusia
yang memiliki inovasi dan kreatifitas yang tinggi serta memiliki kapasitas dan integritas.
Dari manusia yang berinovasi, kreatif dan berintegritas, maka Republik yang kaya
nan subur ini bisa tumbuh dalam meraih cita-citanya sebagai negara welfare state yang dicita-citakan oleh
para founding father.
Pendidikan
Indonesia masa depan juga harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak
bangsa yang sedang menuntut ilmu. Tidak seperti dewasa ini, dimana tempat
pendidikan sangat rawan akan kejahatan. Pemerintah dan seluruh pihak harus
mampu bekerjasama dalam menciptakan suasana aman dan nyaman.
Desain
pendidikan (baca: kurikulum pendidikan) Indonesia harus dipersiapkan dengan
lebih matang, sehingga anak bangsa bisa berkarya dalam membangun bangsa dan
negara ini. Masa depan Republik ini akan menjadi sangat terang benderang ketika
desain pendidikan yang akan dilaksanakan jelas tujuan dan arahnya.
Pemerintahan
Jokowi-JK harus bisa melepas urusan pendidikan dari belenggu kepentingan
politik. Harus dibangun paradigma baru, yaitu politik dengan pendidikan
memiliki arah yang berbeda, sehingga apabila disatukan akan menghasilkan
pertentangan hasil yang tak akan berumur lama. Dengan lepasnya penyusunan
kurikulum pendidikan dari kepentingan politik yang bersifat sementara akan bisa
menghasilkan kurikulum abadi tanpa mengenal siapa pembuatnya dan siapa
berkuasa. Dengan demikian, maka akhirnya Indonesia akan keluar menjadi bangsa
dan negara yang terhormat dimuka bumi karena memiliki generasi emas yang
dihasilkan dari pendidikan yang memiliki landasan kokoh.